Tergelitik dengan tema yang disodorkan, menulis untuk menjaga kesehatan mental bagi perempuan. Menyebabkan muncul banyak pemikiran di kepala saya, apakah laki-laki kesehatan mentalnya tak perlu dijaga? Atau hanya perempuan sajakah yang memiliki permasalahan mental lalu harus bisa menulis untuk bisa mengobatinya? Jadi mereka para perempuan dengan keluhan yang sama akan kesehatan mental tapi tidak bisa menulis bagaimana bisa sembuh?
Satu fakta yang mencengangkan adalah ketika saya menemukan keterangan yang disampaikan Hetih Rusli, editor fiksi Gramedia Pustaka Utama pada sebuah artikel yang dimuat di CNN Indonesia yang menyebutkan kalau para penulis perempuan di Indonesia itu lebih laku.
Sebagai perempuan yang ngakunya juga penulis, mata jadi terasa lebih berbinar, dong. Benarkah penulis perempuan di Indonesia lebih laku? (Bayangan cuan pun langsung berputar di kepala…)
Menyebutkan nama-nama penulis perempuan di Indonesia jauh lebih mudah ketimbang penulis lelaki. Hal itu bisa kejadian mungkin karena jumlah penulis berkelamin perempuan memang lebih banyak. Tapi, konon itu hanya berlaku di Indonesia saja lho!
Kepada CNN Indonesia Hetih menjelaskan, kejadian lebih banyak penulis perempuan dibandingkan penulis laki-laki karena paradigma masyarakat di Indonesia yang masih patrilineal. Patrilineal itu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau ayah.
Mayoritas di Indonesia, masih menganggap urusan mencari nafkah adalah amanat yang diemban para pria. Sementara profesi penulis, masih dianggap profesi sampingan.
Ya sampingan. Lah saya saja meski dua per tiga dari 24 jam keseharian saya dipakai untuk menulis alias ngetik, (melebihi waktu jam kerja pegawai resmi itukan) tetap saja bilang sebagai freelancer. Menulis sebagai hobi. Menulis sebagai pekerjaan sampingan.
Lalu apakah karena itu (jika ada) para laki-laki enggan jadi penulis?
Saya sendiri paham dan merasakan, profesi penulis masih dianggap pekerjaan sampingan. Pekerjaan jadi penulis dianggap enggak akan selamanya bisa jadi harapan tulang punggung keluarga. Semandiri apa pun perempuan, laki-laki tetap punya citra dan tanggung jawab lebih di lingkungan sosial.
Seolah ada pemikiran yang tidak baku kalau pihak laki-laki mau (bekerja) jadi penulis, harus memikirkan apakah penghasilan dari menulis ini bakalan sanggup atau tidak untuk membiayai keluarganya kelak?

Kejadian seperti itu justru kebalikannya jika di negeri Barat seperti Amerika Serikat dan Inggris karena di sana justru lebih banyak penulis berjenis kelamin laki-laki daripada penulis perempuan.
Lihat saja contohnya, penulis seperti Stephen King, John Green, atau Nicholas Sparks secara finansial mereka itu sudah tak perlu pekerjaan utama lainnya karena dengan jadi penulis saja mereka itu sudah sukses.
Secara mereka itu kan dengan royalti dari menulis satu buku saja sudah bisa menghidupi keluarga sampai kenyang banget.
Perlu diketahui kalau oplah penjualan di tanah air dan negeri Barat beda ya. Ibarat bisa terjual 100 ribu eksemplar di luar negeri, sudah termasuk penulis menengah. Mencapainya pun tidak sulit. Sementara untuk di Indonesia, terjual lima ribu eksemplar saja sudah sangat beruntung. Itu pun bisa terjadi dalam waktu tahunan.
Penulis di luar negeri bisa menjual sebanyak 10 ribu itu sudah kayak enggak laku. Lah kalau di kita, bisa jual sebanyak itu sudah bikin selametan.
Kenapa bisa terjadi demikian, mungkin hubungannya dengan minat baca. Keluarga di Indonesia yang berjalan-jalan ke mal lebih memilih membelikan anaknya kopi seharga Rp 40 ribu atau Rp 50 ribu ketimbang buku. Betul kan?
Jadi jangankan generasi mudanya, orang tuanya saja emang sudah ga ada minat baca (dan menulis).
Di negara maju dan negara yang bacaan sudah jadi membudaya seperti Jepang, dunia masyarakatnya di mana-mana baca buku. Sampai anak-anak dibiasakan dan terbiasa membaca buku. Jajan buku buat mereka ibarat jajan es krim. Favorit dan banyak disukai anak.
Di Indonesia, orang lebih memilih ngobrol, chatting, main sosmed, dan browsing daripada membaca buku atau membaca e-book. Karena memang di Indonesia membaca belum menjadi budaya.
Bukan hanya itu, di negeri Barat juga mereka serius mencetak penulis. Ada sekolah khusus untuk belajar menulis sehingga secara teknis dari awal sudah terasah. Sedang penulis Indonesia, bahkan yang sudah menghasilkan karya, masih banyak kesalahan teknis seperti penggunaan titik-koma, tanda kutip, EYD, dan sebagainya.
Itu terbukti saya pernah baca, naskah yang masuk ke redaksi penerbitan di Indonesia, kalau mengikuti standar Amerika, naskah yang masuk bisa ditolak semua.

Terus lagi di sekolah kita, penghargaan terhadap bahasa Indonesia itu kurang. Saya lihat di lingkungan sekolah anak saya saja, para wali murid lebih bangga anaknya bisa bahasa Inggris. Padahal sehari-hari ngomong pakai basa Sunda.
Pengalaman masa kecil saat masih di sekolah dasar, ketika ada pelajaran Bahasa Indonesia dan tugasnya mengarang (biasanya saat masuk setelah liburan sekolah) dari satu kelas berisi 30 orang, hanya dua orang menulis full di kertas folio yang disediakan. Saya dan satu lagi Wina, teman saya yang juga perempuan.
Kembali ke kisah banyaknya penulis perempuan di Indonesia di awal, fenomena ini terjadi sepertinya juga berkaitan dengan perbandingan pengonsumsi novel. Karena perempuan lebih punya banyak waktu, jadi mereka juga lebih banyak jadi pengonsumsi novel ketimbang lelaki.
Semakin banyak yang minat terhadap membaca, maka semakin besar kemungkinan diikuti dengan kegiatannya menulis. Jika banyak perempuan peminat baca semakin banyak juga presentasi perempuan penulisnya.
Keterampilan membaca dan menulis adalah kegiatan yang saling berkaitan. Kemampuan menulis yang baik tidak dapat diperoleh tanpa kemampuan membaca yang baik, karena dengan memiliki kemampuan membaca yang baik seseorang akan mendapatkan informasi yang lebih luas, pengalaman yang didapatkan pun lebih banyak sehingga mampu melahirkan tulisan yang benar, cerita yang sangat menarik dan disukai banyak peminat.
Jika di Indonesia lebih banyak penulis perempuan, sebaliknya, penulis di Amerika Serikat atau Inggris justru kebanyakan membranding diri menjadi ‘lelaki’. Salah satu contohnya: J.K. Rowling. Saat merilis Harry Potter, Rowling menggunakan inisial J.K. agar terlihat seperti nama lelaki.
Padahal mau jenis kelamin perempuan maupun laki-laki, andai mereka tahu bagaimana begitu banyaknya manfaat dari menulis ini, niscaya akan banyak yang mengisi waktu luangnya, dengan menyibukkan diri untuk menulis.
Ya, manfaat menulis itu banyak. Bisa jadi tempat untuk menuangkan ekspresi, tempat untuk meningkatkan kreativitas, ajang latihan dalam memperkuat daya ingat, dengan menulis menjadikan hidup lebih produktif, menulis bisa jadi sebagai ajang media belajar yang baik, dengan menulis bisa terus mengasah diri dalam meningkatkan kemampuan dalam berbahasa dengan baik, dengan membiasakan diri menulis jadwal keseharian menjadi terorganisir, menulis juga bisa jadi alat untuk menghibur diri sendiri maupun yang baca tulisan kita, dan satu lagi nih, menulis itu bisa membantu mengurangi stress.
Saya pernah membaca sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Experimental Psychology, di sana dinyatakan jika menulis tentang pengalaman stres itu dapat membantu mengurangi kecemasan dan membantu orang merasa lebih tenang dan santai.
Karena itu banyak yang bilang menulis sebagai healing, menulis sebagai terapi jiwa, atau menulis sebagai upaya jalan penyembuhan.

Semua itu saya akui kebenarannya. Sedikit rahasia saya ketika berhasil menjuarai lomba kepenulisan, itu saya perhatikan, ternyata kebanyakan momen yang bisa mendapatkan hadiah adalah ketika saya terpuruk dan dalam keadaan diri sedang kecewa.
Mungkin ketika saya sedang down, semangat dan ide yang di mata dewan juri menjadi nilai baik itu muncul dengan maksimal. Ketika terpurydan stress, saya meluapkan segala kemarahan dan kekecewaan dalam bentuk tulisan. Seolah ada yang membimbing bagaimana saya bisa keluar dari tekanan itu untuk bisa membebaskan jiwa yang terkurung raga.
Karena saat menulis, bukankah hati dan pikiran saya bisa bebas mau melanglang buana kemanapun?
Setelah menyadari jika menulis ini bisa jadi sebagai ajang tetapi jiwa, maka menulis bukan lagi sebagai hobi, tapi sudah menjadi obat dan kewajiban.
Ah beneran, rasanya beruntung banget saya ini suka dengan dunia tulis menulis, karena setelahnya, kehidupan yang saya jalani ini jadi bisa terasa lebih waras…

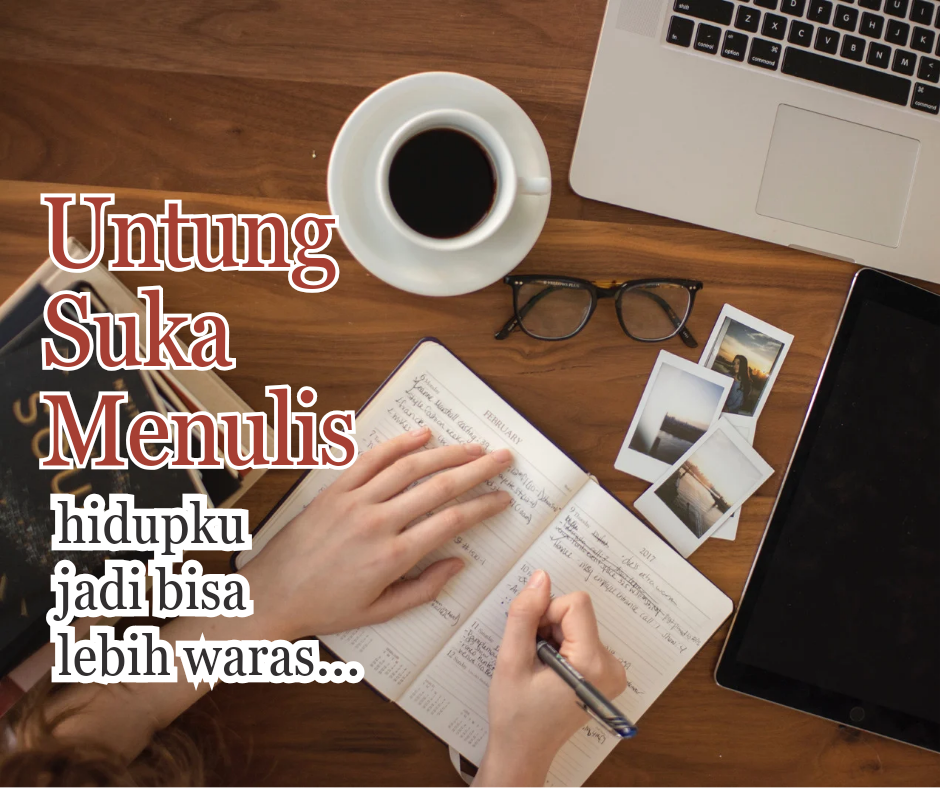

Saya kerjaan utamanya nulis artikel di majalah, dan seneng banget, karena saya suka nulis. Nulis juga pernah saya jadikan sebagai sarana healing dan berdamai dengan bermacam kesusahan, utamanya cerpen dan komedi pendek.
mbaaak … ini sungguh sesuai juga dengan isi hatiku. untuk nulis ya, untuk bisa nulis. untung masih selalu bisa menyempatkan waktu buat nulis, apapun tulisannya. karena aku masih bisa waras dengan menulis
Aku juga beranggapan kalau menulis buatku adalah sebuah terapi jiwa mbak
kadang pas aku stress sama kerjaan, terus nulis diary pengalaman traveling misalnya, itu udah kayak obat buatku
terus BW ke blog temen-temen aja udah bikin aku seneng
Memang bener kalau minat baca masyarakat Indonesia masih sedikit, kayaknya pengunjung toko buku sekarang ini sudah semakin dikit aja mbak, dikotaku soalnya keliatan banget
Kalau dulu pas tahun 90an misalnya atau awal tahun 2000an, yang masuk ke toko buku ramee banget, sekarang yang rame malah mall